Cisungsang, jika ditelusuri artinya, kata tersebut dibentuk oleh dua kata dalam bahasa Sunda, yakni ci dan sungsang. Kata ci merupakan singkatan dari cai yang berarti air, sedangkan sungsang berarti terbalik atau berlawanan dengan keadaan yang seharusnya. Dengan demikian, nama Cisungsang dapat diartikan air yang mengalir kembali ke hulu. Sementara itu dalam Kamus Bahasa Sunda Lama, sungsang merupakan nama sejenis tumbuhan yang berbau dan agak beracun, menyerupai tanaman anggrek. Dalam tradisi Sunda, merupakan satu kelaziman menamai suatu tempat dengan mengambil nama sungai atau tanaman yang banyak tumbuh di sekitar tempat tersebut. Kini, Cisungsang merupakan nama sungai, desa, juga kasepuhan.
Kasepuhan Cisungsang terletak di kaki Gunung Halimun, tepatnya masuk dalam wilayah Desa Cisungsang, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Dari ibu kota Provinsi Banten, yakni kota Serang, menuju Desa Cisungsang harus menempuh jarak sepanjang 200 km, yang setara dengan 5 jam perjalanan. Lokasinya tidak sulit dijangkau karena akses sarana dan alat transportasinya sudah tersedia dengan kondisi yang relatif baik.
Dahulu, tanah Cisungsang dipandang sebagai tanah titipan dari Prabu Walangsungsang. Dia adalah raja Pajajaran yang telah mengalami situasi Ilang Galuh Pajajaran. Dia dipercaya sebagai raja yang tidak mempunyai istana. Kesederhanaannya digambarkan dengan hidup beratap hateup salak dan bertiang cagak agar mudah menempatkan kayu di atasnya. Salah satu keturunannya adalah Mbah Rukman, yang diyakini sebagai orang pertama yang membuka dan membangun Kampung Cisungsang, yang kini telah meluas menjadi sebuah desa, yakni Desa Cisungsang. Tidak kurang dari 9 kampung ada di wilayah Desa Cisungsang, di antaranya Kampung Cipayung, Lembur Gede, Pasir Kapundang, Babakan, Sela Kopi, Pasir Pilar, Gunung Bongkok, Suka Mulya, dan Bojong.
Karakter khas Desa Cisungsang berupa kombinasi antara kampung dan sawah pada daerah lembah yang subur. Sebelum tahun 1960-an, sebagian wilayah Desa Cisungsang diwarnai hamparan huma ‘ladang atau lahan kering yang ditanami padi’. Karena hasil ngahuma dianggap sedikit, lahan persawahan pun dibuka agar dapat memperoleh hasil padi yang maksimal. Ladang ‘huma’ ditinggalkan dan beralih fungsi menjadi kebun yang ditanami buah-buahan, pohon kayu albasiah, dan cengkeh.
Sekarang, Cisungsang sudah menjadi permukiman yang cukup padat, dengan deretan rumah yang tampak berhimpitan satu dan lainnya. Umumnya, rumah-rumah dibangun secara permanen, berdinding bata dan beratap genting. Namun, masih ada sejumlah rumah panggung, yang berbahan baku kayu dan bambu serta beratap nipah. Konstruksi rumah seperti itu, di antaranya tampak di kawasan yang disebut Padepokan Pasir Koja.
 Padepokan Pasir Koja tepat berada di pintu gerbang masuk Desa Cisungsang, dan menempati tanah yang cukup luas di atas lereng perbukitan. Di dalam area tersebut terdapat rumah ketua adat Kasepuhan Cisungsang yang cukup besar. Rumah tersebut menjadi tempat penyelenggaraan berbagai kegiatan adat. Di rumah itu pula, ketua adat menerima tamu dan warga komunitas kasepuhan yang memerlukan bantuannya. Bahkan, tak sedikit dari para tamu yang datang ke sana, mendapat kesempatan untuk menginap di tempat tersebut.
Padepokan Pasir Koja tepat berada di pintu gerbang masuk Desa Cisungsang, dan menempati tanah yang cukup luas di atas lereng perbukitan. Di dalam area tersebut terdapat rumah ketua adat Kasepuhan Cisungsang yang cukup besar. Rumah tersebut menjadi tempat penyelenggaraan berbagai kegiatan adat. Di rumah itu pula, ketua adat menerima tamu dan warga komunitas kasepuhan yang memerlukan bantuannya. Bahkan, tak sedikit dari para tamu yang datang ke sana, mendapat kesempatan untuk menginap di tempat tersebut.
Tidak jauh dari rumah ketua adat, berdiri beberapa rumah panggung berukuran kecil. Penghuninya adalah para pemangku adat yang bekerja membantu kelancaran tugas ketua adat. Di sana juga terdapat lahan persawahan, leuit ‘lumbung padi tradisional’ milik kasepuhan, juga saung lisung ‘tempat menumbuk padi’.
Padepokan Pasir Koja merupakan pusat Kasepuhan Cisungsang. Dari sanalah ketua adat mewarisi dan menjaga tanah titipan karuhun, menjalankan amanat adat, dan melindungi masyarakat dari serangan kebudayaan baru yang sulit dibendung. Selain itu, dari Padepokan Pasir Koja pula dia memimpin masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang, sesuai aturan adat yang menata hubungan sosial antarsesama warga kasepuhan. Aturan tersebut terkristalkan dalam lembaga adat Kasepuhan Cisungsang.
Struktur lembaga adat Kasepuhan Cisungsang diduduki para pejabat adat yang terdiri atas abah (ketua adat), penasehat, dukun, paraji, panei, bengkong, amil, dan rendangan. Pimpinan tertinggi dalam struktur kasepuhan itu adalah abah. Abah adalah sebuah jabatan yang dipegang oleh keturunan dari cikal bakal pembuka Kampung Cisungsang, yakni Mbah Rukman. Keturunan Mbah Rukman adalah orang yang memiliki hak penuh untuk memimpin Kasepuhan Cisungsang atau menjadi ketua adat. Hanya anak laki-laki yang akan mewarisi tampuk kepemimpinan, yang penunjukannya terjadi melalui proses wangsit ‘petunjuk mimpi’ dari leluhur.
Sebagai ketua adat, abah memiliki keahlian dalam bidang pertanian, baik teknis maupun simbolis. Selain itu, dia juga bertindak sebagai pemberi doa dan restu bagi segala kegiatan yang akan dilaksakanan warga Kasepuhan Cisungsang. Jika abah tidak merestui, warga tidak akan berani melanggarnya. Pelanggaran terhadap larangan dari abah dipercaya akan mendatangkan petaka, seperti sakit, gagal dalam aktivitas ekonomi, bahkan hingga meninggal. Jika pelanggaran terlanjur dilakukan, ada ritual khusus yang dapat mencegah pelanggarnya tertimpa musibah. Ritual itu dinamakan lukun, yaitu semacam pengakuan dosa yang dilakukan dengan melaksanakan ritual tertentu disertai doa-doa.
Sampai saat ini, kepemimpinan di Kasepuhan Cisungsang telah mencapai empat generasi. Nama-nama ketua adat dari generasi pertama hingga yang keempat adalah Embah Buyut yang mencapai usia sekitar 350 tahun, Uyut Sarkim yang berusia sekitar 250 tahun, Olot Sardani yang berumur 126 tahun; dan Abah Usep. Dalam menjalankan tugasnya, abah dibantu seorang penasihat, yang bertugas memberikan berbagai pertimbangan, dan sekaligus sebagai utusan abah yang melaksanakan tugas-tugas kasepuhan. Kedua pemimpin adat itu juga dibantu beberapa orang yang memiliki keahlian khusus. Mereka terdiri atas dukun, yakni orang yang bertanggung jawab menangani kesehatan, ritual pertanian, dan siklus hidup; paraji, yakni seorang perempuan yang bertanggung jawab menangani masalah kehamilan, persalinan, dan perawatan bayi; panei, yakni orang yang bertanggung jawab menyediakan perkakas kerja dalam bidang pertanian dan kebun; bengkong, yakni orang yang bertanggung jawab menangani dan membantu masyarakat dalam acara khitanan. amil, orang yang bertanggung jawab menangani dan membantu masyarakat dalam urusan pengelolaan zakat, pernikahan, kematian, dan kelahiran. Dalam hal ini, dia bekerja sama dengan aparat pemerintahan desa serta kecamatan; yang terakhir adalah rendangan, yaitu orang yang ditunjuk secara turun temurun menjadi wakil abah di sejumlah kampung .
Masyarakat Kasepuhan Cisungsang merupakan kelompok suku Sunda, Oleh karena itu, bahasa Sunda sebagai bahasa pengantar dalam kehidupan sehari-hari. Mereka juga mampu berbahasa Indonesia relatif baik jika harus berkomunikasi dengan tamu yang bukan orang Sunda. Selain melalui pendidikan formal, kemampuan berbahasa Indonesia semakin terasah dari mereka yang merantau untuk bekerja mencari nafkah di kota-kota besar, seperti Jakarta dan Sukabumi.
Sekalipun ada warga masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang yang bekerja jauh dari tempat asalnya, mata pencaharian utama mereka umumnya adalah bertani. Ada juga yang bekerja sebagai pedagang, pekerja perusahaan tambang, menjadi pegawai negeri, dan buruh di kota-kota besar, seperti Jakarta dan Sukabumi.
Khusus untuk kegiatan bertani, abah berperan sebagai komando yang harus diikuti oleh warganya. Dengan kata lain, dalam setiap sesi pertanian selalu diawali oleh abah kemudian baru diikuti oleh warga. Proses ini menjadi semacam upaya pelestarian tradisi bertani yang diwariskan leluhur, sekaligus juga menjadi filter bagi teknologi pertanian baru yang akan masuk dalam pertanian di Kasepuhan Cisungsang. Dalam beberapa hal, abah cukup akomodatif mengadopsi program pemerintah di bidang pertanian, selama hal itu tidak akan mengganggu tatanan harmoni kehidupan yang telah digariskan leluhur.
Aktivitas pertanian masyarakat Kasepuhan Cisungsang sarat dengan kearifan lokal, baik dalam wujud pengetahuan maupun tradisi bertani. Ada pantangan-pantangan yang harus dipatuhi, ada pula beragam ritual upacara tradisional yang senantiasa menyertai setiap tahapan aktivitas pertanian. Beberapa upacara tersebut adalah upacara Nibakeun Sri ka Bumi, Ngamitkeun Sri ti Bumi, Ngunjal, Rasul Pare di Leuit, dan Seren Taun.
Pelaksanaan upacara tradisional tadi biasanya diwarnai dengan pertunjukan kesenian tradisional. Sedikitnya ada dua jenis kesenian yang digelar, seperti angklung buhun dan dog-dog lojor. Fungsinya bukan semata-mata sebagai hiburan, melainkan juga sebagai penolak bala untuk mengusir kekuatan buruk yang akan mengganggu kelancaran pelaksanaan kegiatan bertani. Khusus dalam upacara Seren Taun, tidak hanya dua kesenian yang ditampilkan tetapi melibatkan hampir semua jenis kesenian tradisional yang ada di wilayah Kasepuhan Cisungsang. Kesenian tradisional yang hidup dan berkembang di wilayah itu adalah angklung buhun, dogdog lojor, sisindiran atau pantun, ngagondang, wayang golek, ujungan, silat baster, rengkong, celempung, karinding, dan betok.
Masih ada ritual upacara lainnya yang diselenggarakan masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang, selain ritual upacara pertanian. Sejumlah upacara tersebut meliputi upacara bulan purnama yang dilaksanakan 12 kali dalam setahun saat bulan purnama pada tanggal 14; upacara ngukus di padaringan setiap Minggu malam dan Rabu malam; upacara prah-prahan, yang dilaksanakan untuk membuat penolak bala berupa sawen, pada Jumat pertama bulan Muharam; upacara Rasul Mulud, yang dilaksanakan pada hari Senin atau Kamis setelah tanggal 14 pada bulan Mulud; dan upacara munar lembur yang dilaksanakan lima tahun sekali.
Masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang masih memelihara religi atau kepercayaan leluhurnya yang termanifestasikan dalam adat istiadat mereka. Berbagai aspek kehidupan diwarnai dengan aturan adat, seperti dalam membangun rumah, berkaitan dengan daur hidup manusia, dan aktivitas ekonomi. Yang lebih utama lagi, mereka menjalankan aktivitas peribadatan sesuai keyakinan yang dianutnya, yakni agama Islam. Dalam hal ini, agama dan tradisi berjalan seirama mengatur kehidupan warga masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang.


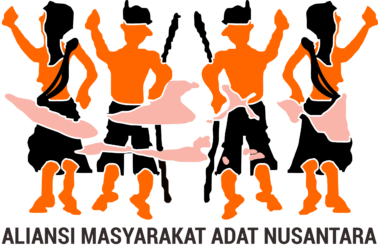






 lar memiliki keterikatan sejarah dengan salah satu kerajaan Sunda dengan rajanya Prabu Siliwangi, Kasepuhan Banten Kidul, dengan pusat pemerintahan berada di wilayah Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Kampung Gede Ciptagelar, Cikarancang, Cicemet, Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi. Masyarakat yang tinggal di Kampung Ciptagelar disebut masyarakat kesepuhan. Kata kasepuhan mengacu pada golongan masyarakat dengan aturan adat istiadat lama. Masyarakat Kampung Ciptarasa menyebut diri sebagai Kasepuhan Pancer Pangawinan, serta merasa kelompoknya sebagai keturunan Prabu Siliwangi.
lar memiliki keterikatan sejarah dengan salah satu kerajaan Sunda dengan rajanya Prabu Siliwangi, Kasepuhan Banten Kidul, dengan pusat pemerintahan berada di wilayah Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Kampung Gede Ciptagelar, Cikarancang, Cicemet, Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi. Masyarakat yang tinggal di Kampung Ciptagelar disebut masyarakat kesepuhan. Kata kasepuhan mengacu pada golongan masyarakat dengan aturan adat istiadat lama. Masyarakat Kampung Ciptarasa menyebut diri sebagai Kasepuhan Pancer Pangawinan, serta merasa kelompoknya sebagai keturunan Prabu Siliwangi.
 Padepokan Pasir Koja tepat berada di pintu gerbang masuk Desa Cisungsang, dan menempati tanah yang cukup luas di atas lereng perbukitan. Di dalam area tersebut terdapat rumah ketua adat Kasepuhan Cisungsang yang cukup besar. Rumah tersebut menjadi tempat penyelenggaraan berbagai kegiatan adat. Di rumah itu pula, ketua adat menerima tamu dan warga komunitas kasepuhan yang memerlukan bantuannya. Bahkan, tak sedikit dari para tamu yang datang ke sana, mendapat kesempatan untuk menginap di tempat tersebut.
Padepokan Pasir Koja tepat berada di pintu gerbang masuk Desa Cisungsang, dan menempati tanah yang cukup luas di atas lereng perbukitan. Di dalam area tersebut terdapat rumah ketua adat Kasepuhan Cisungsang yang cukup besar. Rumah tersebut menjadi tempat penyelenggaraan berbagai kegiatan adat. Di rumah itu pula, ketua adat menerima tamu dan warga komunitas kasepuhan yang memerlukan bantuannya. Bahkan, tak sedikit dari para tamu yang datang ke sana, mendapat kesempatan untuk menginap di tempat tersebut.